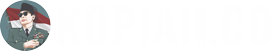Indonesia, pada dasarnya, adalah sebuah imajinasi yang disepakati. Ia tidak lahir dari kesamaan darah, melainkan dari kesatuan cita-cita dan keberanian membayangkan diri sebagai satu bangsa. Sumpah Pemuda 1928 menjadi titik kristal dari kesadaran itu—sebuah momen ketika bahasa, tanah air, dan kebangsaan dilebur menjadi satu tekad yang melampaui batas kolonial. Namun, hampir seabad kemudian, imajinasi kebangsaan itu menghadapi bentuk ujian baru. Dunia digital menciptakan manusia yang sangat terhubung, tetapi sekaligus sangat terpisah. Paradoks ini, sebagaimana dikatakan Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society, melahirkan network society—masyarakat jaringan yang efisien secara informasi, tetapi rapuh secara sosial.
Benedict Anderson dalam Imagined Communities menegaskan bahwa bangsa adalah “komunitas politik yang dibayangkan”—sebuah kesadaran yang tumbuh karena manusia mampu membayangkan dirinya hidup bersama mereka yang tak pernah ditemuinya. Dalam konteks Indonesia, bahasa menjadi medium utama dari imajinasi tersebut. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia berperan sebagai lingua franca yang melintasi batas etnik dan sosial-ekonomi, mempersatukan keragaman motif perjuangan, agama, suku, hingga ekonomi—menjadi cita-cita tunggal: kemerdekaan.
Namun di era digital, bahasa justru kehilangan daya integratifnya. Ia menjadi alat retorika dan performa di media sosial, tempat identitas sering kali dipertentangkan, bukan dipersatukan. Bahasa yang dulu menjadi jembatan kini berubah menjadi pagar. Fenomena ujaran kebencian, rasisme antar suku, dan polarisasi politik di ruang digital menunjukkan bahwa bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasi yang membangun kesadaran bersama, tetapi senjata yang mengukuhkan sekat-sekat identitas. Dalam pengertian Anderson, narasi kebangsaan terancam redup karena bahasa—yang dulu menjadi penopangnya—kini kehilangan daya imajinatif untuk menyatukan.
Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengajarkan bahwa peradaban bertahan karena adanya ‘asabiyyah—solidaritas sosial yang menjadi perekat masyarakat. Ketika ‘asabiyyah melemah, bangsa akan terpecah dan kehilangan arah. Jika dulu solidaritas Indonesia tumbuh dari penderitaan bersama di bawah kolonialisme, kini ia diuji oleh dunia maya yang membentuk solidaritas semu. Dunia digital menciptakan ilusi kedekatan, tetapi sekaligus memperkuat polarisasi melalui algoritma yang mempersempit pandangan dan menumbuhkan fanatisme baru. Ibn Khaldun seperti berbicara pada zaman ini: kehancuran bangsa bukan datang dari luar, melainkan dari rapuhnya solidaritas batin di dalam.
Soekarno, dalam Di Bawah Bendera Revolusi, menulis bahwa nasionalisme sejati adalah yang “memberi hidup kepada kemanusiaan, bukan menindasnya.” Baginya, cinta tanah air tidak boleh berhenti pada batas geografis, melainkan harus berakar pada keadilan sosial dan kemanusiaan universal. Namun di era kapitalisme digital, seperti digambarkan Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism, nilai-nilai kemanusiaan itu kerap direduksi menjadi data, algoritma, dan citra diri. Semangat gotong royong tergantikan oleh logika kompetisi dan representasi virtual.
Barangkali di sinilah krisis terbesar kita hari ini: kita tidak lagi mengalami sumpah itu, hanya menghafalnya. Kita memperingati tanggalnya, tetapi melupakan maknanya. Kita tahu teksnya, tapi kehilangan rasa getir di balik kalimat-kalimatnya. Sumpah Pemuda, pada akhirnya, bukanlah dokumen sejarah yang selesai dibaca, melainkan proyek moral yang menunggu untuk dijalankan ulang di setiap generasi.
Maka, menafsir ulang Sumpah Pemuda hari ini bukan soal mengulang kata-katanya, tapi menghidupkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya: keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kerendahan hati untuk mengakui perbedaan, dan kesetiaan untuk terus merawat kebersamaan. Tiga butir ikrar itu bukan dogma, tapi etika: satu nusa sebagai tanggung jawab ekologis; satu bangsa sebagai komitmen sosial; dan satu bahasa sebagai kesetiaan terhadap kebenaran.
Kita mungkin tak lagi duduk di gedung Kramat Raya 106 seperti para pemuda 1928. Tapi setiap kali kita memilih menghargai perbedaan, menolak intoleransi, dan berbicara jujur di tengah kebohongan massal, di sanalah Sumpah Pemuda terlahir kembali. Bukan hanya melalui pidato, melainkan juga melalui tindakan.
Sumpah itu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk kita hidupkan lagi, di jalan-jalan, di ruang belajar, di dunia maya, dan di hati yang percaya bahwa bangsa ini masih mungkin bersatu. Sebab, seperti yang ditulis Muhammad Yamin nyaris seabad silam, “Kini bangsaku, insafkan diri—berjalan ke muka, marilah mari.”
Penulis: Muhammad Sheva Maulaya Zuhdi (Mahasiswa S1 Universitas Zaitunah, Kairouan)