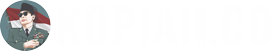Kopiah.Co — Pendidikan Indonesia kembali mengalami masalah yang bersifat repetitif. Tahun ini, pemerintah merencanakan perubahan kebijakan terkait penerapan paradigma pendidikan di Indonesia. Dari yang semula adalah “Kampus Merdeka”, kemudian berubah terminologi menjadi “Kampus Berdampak”. Tentunya, permasalahan ini merupakan suatu kondisi yang sudah mendarah daging dalam penerapan sistem pendidikan tanah air. Alih-alih memfokuskan diri terhadap pembangunan kerangka filosofis pendidikan yang fundamental, pemerintah malah terjerembap dalam pembangunan paradigma pendidikan yang cenderung reaksioner, dan terpaku pada perubahan politik juga perkembangan birokrasi.
Perubahan Paradigma pendidikan ini, tentunya perlu diperhatikan secara seksama oleh pemangku kebijakan pendidikan nasional. Karena, perubahan terminologi dari “merdeka” ke “berdampak” ini tidak hanya menyasar fragmen bahasa, tetapi juga mengarah kepada perubahan orientasi pendidikan, dari kemerdekaan ke arah pemberian dampak terhadap sosial.
Hal ini, mencerminkan bahwa Indonesia dalam menyusun kerangka paradigma pendidikan nasional, cenderung dinamis dan fleksibel. Sehingga, membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki paradigma pakem dan tidak memiliki kestabilan arah yang dapat menunjang proses kemajuan bangsa. Akibatnya, Pendidikan Indonesia dapat dianalogikan melaju selayaknya kereta tanpa masinis, atau kapal tanpa nahkoda.
Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu berdampak terhadap kinerja dan kemampuan guru-guru di seluruh lembaga pendidikan. Baik dari sekolah dasar, hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam kurun waktu kurang lebih dari satu dekade, para pengajar sudah harus beradaptasi dengan paradigma pendidikan baru yang diterapkan pemerintah sekonyong-konyong. Alih-alih menyatupadukan antara kemerdekaan dan kebermanfaatan (berdampak), Indonesia malah menciptakan dikotomi baru dalam tatanan paradigma pendidikan nasional. Paulo Freire dalam Pedagogy of The Opressed (1970) menyatakan bahwa pendidikan yang membebaskan dan memerdekaan tidak cukup untuk hanya mengembangkan potensi individu. Tetapi juga harus diimbangi oleh pendidikan yang bersifat transformatif dan reflektif.
Antara Kebebasan dan Kebermanfaatan
Sebetulnya, Kurikulum “Merdeka Belajar” yang sudah diadakan selama kurun waktu satu dekade ini memberikan angin segar di dunia pendidikan nasional. Hal ini, tentunya diharapkan agar paradigma pendidikan nasional dapat memberikan warna yang beragam terhadap kemampuan pembelajar. Sehingga, dapat menghasilkan para pembelajar yang spesialis di berbagai lintas jurusan dan juga beragam kemampuan. Dalam tradisi filsafat pendidikan misalnya, Jean Paul Sartre seorang eksistensialis Perancis, menekankan bahwa pendidikan harus memberikan ruang kebebasan kepada tiap individu untuk menentukan sendiri arah pendidikan tersebut.
Di sisi lain, kebermanfaatan dan pemberian dampak dari pendidikan menjadi salah satu fragmen penting yang harus diperhatikan. Sehingga, apa yang dihasilkan dari pendidikan dapat dirasakan secara reflektif dan menjadi pengalaman berharga dari proses pembelajaran. Merujuk kepada pendapat John Dewey dalam Democracy and Education (1916) yang berpendapat bahwa pendidikan yang berorientasi pengalaman akan membentuk warga negara yang aktif, berpikir kritis, dan demokratis. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan partisipasi sosial.
Maka dari itu, sebetulnya perpaduan antara merdeka dan berdampak bukanlah sebuah hal yang kontradiktif. Jangan malah membuat sebuah dikotomi cuma-cuma yang memicu problematika baru pendidikan dalam negeri. Masih ada beragam masalah lain seperti, komersialisasi pendidikan, upah guru, dan lain-lain yang harus segera ditangani.
Sebuah laporan Future of Jobs 2023 dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kemampian berpikir kritis, kreativitas,dan fleksibilitas justru menjadi penentu daya saing masadepan. Maka, konsep perpaduan antara merdeka dan berdampak akan memiliki daya saing yang signifkan, daripada harus menyingkirkan salah satu paradigma tersebut.
Antara Eksplorasi dan Spesialisasi
Salah satu yang menjadi episentrum pembahasan perubahan paradigma pendidikan adalah reaktivasi penjurusan ke IPA, IPS, dan bahasa. Tentunya, ini menimbulkan sebuah unsur kontradiksi baru antara esensi yang ingin dimunculkan dari paradigma merdeka maupun berdampak.
Pada sisi “Merdeka Belajar”, tentunya program tersebut berlainan dengan nilai-nilai kemerdekaan. Dimana seorang pembelajar dipaksa untuk dapat fokus pada sebuah spesialisasi yang sudah ditentukan. Pierre Bordieu dalam karyanya Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) mengutip bahwa “Academic choices are not the product of individual aptitudes or interests, but are largely predetermined by social origin.” Artinya, bahwa pemilihan akademik tidak ditentukan dari minat atau bakat individu, melainkan berdasarkan modal sosial, modal kultural, serta habitus -sebuah struktur mental yang dibentuk dari pengalaman sosial- tiap individu.
Di seberang jalan lainnya, terminologi “berdampak” juga perlu diterapkan sehingga nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, pendidikan yang tidak menindas, dan kesetaraan pendidikan dapat tercapai. Misalnya, Paulo Freire di dalam Pedagogy of The Opressed (1970) menyatakan bahwa pendidikan harus dibangun atas dasar kemampuan yang dialogis dan reflektif.
Maka misalnya, paradigma pendidikan berdampak perlu mempertimbangkan aspek-aspek aplikatif dan produktif yang dapat memberikan dampak pembangunan nasional. Dan hal tersebut, dapat terlihat dalam aspek-aspek akumulatif seperti, meningkatnya minat baca, meningkatnya indeks pendidikan nasional, dan lain-lain.
Tentunya, dalam proses pencanangan pembangunan paradigma Pendidikan nasional, Pemerintah harus terlebih dahulu fokus terhadap kerangka filosofis pendidikan. Sehingga, paradigma pendidikan nasional tidak berubah seiring berubahnya pimpinan. Pendidikan tidak lagi menjadi korban dari perubahan cuaca politik dalam negeri.Di samping itu, proses kolaborasi dan perpaduan antar paradigma juga perlu diutamakan, sehingga apa yang sudah baik dan terstruktur sebelumnya dapat dioptimalisasikan dengan kebijakan yang hadir di kemudian hari. Sehingga, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, pendidikan tidak hanya menjadi aspek yang omon-omon belaka, tetapi menjadi pionir penting arah kemajuan suatu bangsa.
Dalam pidato “Lahirnya Pancasila” pada 1 Juni 1945, Bung Karno menekankan pentingnya membentuk manusia Indonesia yang merdeka dan berkepribadian. Bung Karno sang guru bangsa dengan jelas menekankan, bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia merdeka. Yaitu manusia yang merdeka pikirannya, jiwanya, dan tindakannya.