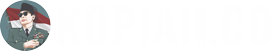Kopiah.Co– “Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, My nationalism is humanity”… kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa …. Inilah filosofisch principle yang nomor dua,… yang boleh saya namakan “internasionalisame’’. Tetapi jikalau saya katakan interasionalisme, bukanlah saya yang bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak mau adanya kebangsaan…” (Sukarno, 1 Juni 1945)
Petikan dari ungkapan Bung Karno di atas menegaskan bahwa dunia yang ingin dibangun oleh Bung Karno adalah dunia yang menjadi tempat aman dan damai bagi seluruh manusia. Bagi Bung Karno sebagaimana ditulis oleh Yudi Latif dalam bukunya bukunya Negara Paripurna bahwa semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan universal serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Gagasan tentang kemanusiaan universal ini menjadi tema sentral yang diperjuangkan Soekarno sejak permulaan pergerakannya di dunia politik, terutama perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda.
Bahkan, pasca Indonesia Merdeka visi kemanusiaan universal yang digagas Seokarno itu tidak pernah mati, ditandai dengan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang mendorong kemerdekaan bagi negara-negara terjajah di Kawasan Asia Afrika, salah satunya Tunisia. Majalah harian As-Syabab yang diterbitkan pada Mei 1960 di Tunisia menuliskan dengan tinta emas bahwa Soekarno adalah tokoh sentral yang menjadi pejuang kemerdekaan Tunisia dalam Bahasa Arab disebut wissam al-mujahidin. Hal inilah yang menjadi komitmen Bung Karno selama hidupnya dalam rangka membangun peradaban dunia di mana semua penduduknya hidup dalam damai dan persaudaraan.
Gerakan kemanusiaan universal yang digagas oleh Soekarno ini sejatinya tidak lepas dari nilai-nilai etis ketuhanan yang memimpin cita-cita negara kita, sebagaimana disebut oleh Yudi Latif dalam ungkapan Hatta dalam pidatonya pada tahun 1956 di Universitas Gadjah Mada, “Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia harmoni di dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persahabatan antara manusia dan bangsa”. Maknanya, nilai Ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila itu, tidak berhenti pada ruang ibadah formal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga meniscayakan sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.
Syeikh Muhammad Thahir bin Asyur dalam bukunya Pranata Sosial dalam Islam mengatakan bahwa, visi utama hadirnya agama di muka bumi adalah mengatur tatanan dunia dengan baik dan mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis bagi penduduknya. Nilai-nilai Islam inilah yang barangkali mengilhami Soekarno sehingga agama yang dipahaminya adalah sebuah agama yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan anti penindasan.
Melalui tulisan ini, saya tertarik membicarakan tentang gagasan kemanusiaan universal dalam pandangan Sukarno dan ulama besar Tunisia, Syeikh Muhammad Thahir bin Asyur. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi, mengapa saya menyebutkan dua tokoh ini. Pertama, Sukarno dan Ibnu Asyur adalah dua tokoh penting bagi kemerdekaan negaranya masing-masing, yakni Indonesia dan Tunisia. Kedua, Sukarno dan Ibnu Asyur adalah dua tokoh yang hidup di era yang sama, yaitu abad 20, Dimana masing-masing tokoh ini menghadapi masalah yang sama, yakni penjajahan. Ketiga, Sukarno dan Ibnu Asyur adalah dua tokoh yang meniscayakan pentingnya membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun peradaban dunia yang damai.
Pada tulisan ini, penting juga bagi kita mengetahui jejak perjuangan Sukarno dan Ibnu Asyur dalam mewujudkan kehidupan umat manusia yang merdeka, bersaudara, dan harmonis dengan mengenal perjalanan pergerakannya.
Pergerakan Kemanusiaan Sukarno
Pergerakan Sukarno penuh diwarnai dengan spirit kemanusiaan dan kebebasan yang mengalir di jiwanya membuat bangsanya Indonesia ingin terlepas dari kolonialisme. Hal ini terjadi dalam perjalanan menuju Bandung Selatan yang kemudian bertemu dengan soerang petani. Jiwa muda Sukarno bergejolak ketika melihat sosok petani yang Bernama Bapak Marhaen, petani tersebut mempunyai beberapa lahan pertanian dan cangkul sendiri yang ia olah sendiri, akan tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Seperti yang ditulis oleh Hasto Kritiyanto di dalam bukunya Suara Kebangsaan, sosok petani Bernama Pak Marhaen itulah refleksi suara kebangsaan Bung Karno. Mewakili jutaan petani bumi putra lainnya, petani itu miskin karena terjajah tata pergaulan hidup yang mengisap.
Tentu ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kondisi ini kemudian menyulut berbagai pertanyaan dan akhirnya melahirkan pemikiran sebagai landasan pergerakan-pergerakan selanjutnya. Di sini Sukarno tertitik pada orang tertindas padahal dia hidup di tanah yang subur. Pada saat masa kolonial banyak rakyat Indonesia yang tertindas, lahan mereka terampas, tentu tak kala melihat rakyat Indonesia diperlakukan dengan beringas membuat Bung Karno geram tak terkira. Seperti yang ditulis oleh Hasto Kristiyanto di dalam bukunya Suara Kebangsaan, dalam analogi Bung Karno mengambil contoh sederhana, cacing saja, jika terinjak, akan kluget-kluget melakukan perlawanan. Apalagi suatu bangsa terjajah.
Suara-suara kemanusiaan ini terus digaungkan secara massif, di berbagai lapisan rakyat Indonesia. Sebagai muslim tentu saja Bung Karno menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup, terutama pada teladan dalam sisi kemanusiaan. Bagi Bung Karno Nabi Muhammad SAW merupakan The Greatest Man in History yang telah melakukan revolusi-revolusi salah satunya adalah revolusi kemanusiaan yang berdampak pada kerangka pranata sosial Islam bahkan dunia. Seperti yang dikemukakan dalam salah satu pidatonya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, 12 Juni 1965 di Istana Negara. Sebut saja ketika Nabi Muhammad SAW merevolusi kesamaan nilai kemanusiaan antara Laki-laki dan Perempuan. Hal ini kemudian diadopsi oleh Bung Karno dengan keselarasan kondisi rakyat Indonesia yang menjadi spirit pergerakannya.
Tren mengaungkan kemanusiaan menjadi tren positif untuk negara-negara terjajah. Bung Karno menjadi influencer bagi negara-negara yang bernasib sama seperti Indonesia khususnya negara-negara di Kawasan Asia dan Afrika. Gerakan yang menolak segala macam bentuk imperialism dan kolonialisme bermunculan seperti GNB (Gerakan Non-Blok). Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang diadakan pada tahun 1995 dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Seperti yang ditulis Hasto Kristiyanto di Suara Kebangsaan, diksi kemanusiaan telah membuat para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, merumuskan tesis sederhana, bahwa kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah jalan dan “jembatan emas” untuk membebaskan manusia Indonesia dari belenggu penjajahan, segala penjajahan yang mengerdilkan harga diri sebagai bangsa.
Indonesia bukan hanya menjadi “jembatan emas” untuk rakyatnya sendiri, tetapi juga menjadi “jembatan emas” untuk bangsa-bangsa yang bernasib sama yang terbelenggu rantai imperialisme dan kolonialisme yang melahirkan persaudaraan dunia di dalam merealisasikan kemanusiaan tanpa melihat latar belakang bangsa, suku, dan budaya. Seperti penolakan penjajahan Israel terhadap Palestina, Bung Karno berkata “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel”. Pada saat, Bangsa Indonesia tidak membuka hubungan diplomasi sebagai bentuk penolakan penjajahan Israel terhadap Palestina.
Ibnu Asyur, Ulama Ensiklopedis Humanis Tunisia
Humanisme merupakan diskursus penting dalam dunia pemikiran, khususnya pemikiran Islam, karena Islam sangat menjujung tinggi kemanusiaan. Seperti halnya Indonesia, di belahan benua lain pun sedang gencar menggaungkan kemanusiaan, terutama di Kawasan Timur Tengah. Sebagai mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Tunisia, banyak pemikiran ulama-ulama besar humanis yang syarat akan nilai-nilai humanis di karya-karya mereka.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Syeikh Muhammad Thahir bin Asyur telah mengemukakan visi utama hadirnya agama di muka bumi, yaitu mengatur tatanan dunia dengan baik dan mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi penduduknya. Banyak goresan tinta emas yang menyuarakan prinsip humanisme dalam karya-karya beliau. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Asyur dalam kitabnya Maqashid Syariah al-Islamiyah menegaskan bahwa tasyri’ hukum islam yang sesuai dengan maksud islam bertujuan untuk menunjukan keagungan islam itu sendiri; bahwa Islam sejatinya turut menjaga tegaknya maslahat dan mencegah kemudharatan. Lebih dari itu, yang lebih penting tasyri’ hukum Islam berperan dalam menciptakan keteraturan dan perbaikan di masyarakat.
Melalui karyanya ‘Allamah Ibnu Asyur menambahkan beberapa nilai universal yang harus memprioritaskan kemaslahatan individual dan sosial. Di antaranya adalah fitrah (naturalis), samhah (toleran), musawah (kesetaraan), taisir (kemurahan), dan hurriyah (nilai kebebasan). Hal ini juga senada apa yang ditulis dalam buku Pranata Sosial dalam Islam yang menjelaskan tentang visi agama di dunia, bagaimana Islam berkontribusi dalam berdirinya pranata sosial di masyarakat, individu-individunya, toleransi, kesetaraan, persaudaaran sesama muslim, keaadilan, dan lain sebagainya.
Melalui karyanya yang disusun dalam Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah Ibnu ‘Asyur mengkaji lebih detail tentang prinsip universal. Yang pertama Al-Fitrah, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Kemudian Al-Samhah dengan sifat ini seseorang dapat memposisikan segala sesuatu seimbang antara sikap berlebihan dan terlalu menggampangkan. Yang ketiga Al-Musawah Islam adalah agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum syari’ diberlakukan sama. Kemudian Al-Taisir bahwa di setiap segala sesuatu ada kemudahan. Dan yang terakhir Al-Hurriyah menurut Ibnu ‘Asyur , ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya maka disitulah ditemukan sifat Al-Hurriyah.
‘Allamah Ibnu Asyur mengemukakan bagaimana mereformasi setiap individu masyarakat. Bagi Ibnu Asyur pembaharuan budi pekerti merupakan landasan untuk pembenahan seluruh akhlaknya, dan setelah itu barulah upaya pembenahan perbuatannya, dan kedua pembenahan tersebut merupakan fokus menjadikan masyarakat Islam mencapai keharmonisan.
Apa yang disampaikan oleh Syeikh Ibnu ‘Asyur adalah interpretasi di dalam mencapai individu dan masyarakat yang bersatu dan harmonis. Gagasan tentang persatuan dan keharmonisan telah muncul sejak ia dilahirkan di bumi, akan tetapi untuk dalam luasnya ambisi dan kurangnya kemampuan manusia mereka butuh bantuan satu dengan lainnya dan saling melengkapi. Dengan demikian manusia tentu adalah makhluk sosial yaitu membutuhkan persatuan dan kasih sayang agar dapat mencapai keharmonisan. Dari pemikiran inilah muncul sistem kekeluargaan, yaitu suatu kelompok kecil dari garis keturunan keluarga, kemudian sistem kesukuan, dan yang lebih menyeluruh yaitu sistem kebangsaan.
Menurut Ibnu Khaldun konsep ini disebut ’ashabiyah, yang membentuk solidaritas sosial masyarakat untuk saling berkolaborasi, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban sesama manusia. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Heterogenitas dalam masyarakat yang terdiri dari banyak suku dilebur ke dalam suatu cita-cita dan mimpi besar yang kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan peradaban yang jangkauannya melampaui batas teroteri, dan batas etnis. Dengan demikian segala bentuk perbuatan yang mengusik keharmonisan, keamanan, kebebasan seseorang harus dihapuskan dengan segera, karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan esensi universal dari Islam.
Titik Temu Sukarno dan Ibnu Asyur: Kemanusiaan Universal sebagai Cita-cita
Di persimpangan abad ke-20, sejarah mempertemukan dua tokoh yang lahir dari tanah dan zaman berbeda, namun dipersatukan oleh denyut cita-cita yang sama: Sukarno, proklamator kemerdekaan Indonesia yang lantang menyuarakan solidaritas bangsa-bangsa, dan Muhammad Thahir bin ‘Ashur, ulama besar Tunisia yang mewariskan karya monumental Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah. Meski medan perjuangan keduanya berbeda—Sukarno di gelanggang politik kebangsaan dan internasional, Ibnu Asyur di arena keilmuan dan reformasi hukum Islam—ada satu poros yang menyatukan langkah mereka: keyakinan bahwa kemanusiaan universal adalah cita-cita yang harus diperjuangkan.
Sukarno tumbuh di tengah arus kolonialisme yang merampas martabat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Bagi dirinya, kemerdekaan bukan sekadar pergantian bendera atau pengusiran penjajah, melainkan kelahiran sebuah tatanan dunia yang adil, setara, dan menghormati harkat manusia. Pandangan ini terpatri dalam pidato-pidatonya, terutama ketika ia berdiri di podium Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, menyerukan persatuan negara-negara baru yang merdeka, melampaui batas geografi, ras, dan agama. Ia menolak dikotomi yang memecah dunia menjadi Barat dan Timur, utara dan selatan, karena yang ia perjuangkan adalah ruang hidup bersama yang dibangun atas dasar keadilan dan persaudaraan.
Ribuan kilometer dari Indonesia, Ibnu Asyur hidup di Tunisia yang kala itu berada di bawah protektorat Prancis. Ia menyaksikan bagaimana umat Islam terjebak dalam formalitas hukum yang kaku, sehingga kehilangan ruh ajaran yang sejatinya membawa rahmat bagi seluruh alam. Melalui karya besarnya, Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah, ia merumuskan kembali tujuan-tujuan luhur syariah yang selama ini terkubur di balik perdebatan teknis. Baginya, inti syariah adalah kemaslahatan umum—al-maslahah al-‘āmmah—yang tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan keyakinan atau asal-usulnya. Syariah, menurutnya, harus menjadi jembatan untuk menjaga kehidupan, kehormatan, akal, dan kebebasan manusia.
Jika Sukarno merumuskan Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa, Ibnu Asyur merumuskan maqāṣid sebagai jiwa dari seluruh bangunan hukum Islam. Dalam keduanya, nilai kemanusiaan menempati posisi sentral. Sila kedua Pancasila—Kemanusiaan yang adil dan beradab—mencerminkan prinsip etik-politik yang menuntut negara untuk menghapuskan segala bentuk penindasan. Sementara dalam kerangka maqāṣid, perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) adalah manifestasi dari keharusan menjaga martabat manusia secara universal.
Sukarno memandang kemerdekaan sebagai milik setiap bangsa, bukan hak istimewa segelintir negara kuat. Ibnu Asyur memandang kemaslahatan sebagai hak setiap manusia, bukan hanya komunitas Muslim. Keduanya sama-sama menolak eksklusivisme—Sukarno menolak nasionalisme sempit yang menafikan solidaritas internasional, Ibnu Asyur menolak tafsir agama yang membatasi rahmat hanya pada satu golongan.
Dalam pandangan mereka, pendidikan menjadi salah satu pilar terpenting. Sukarno yakin bahwa kebodohan adalah sekutu setia kolonialisme; ia mendorong pendidikan massal untuk membangun kesadaran kebangsaan. Ibnu Asyur juga menekankan reformasi pendidikan (iṣlāḥ al-ta‘līm) agar generasi Muslim memahami substansi ajaran, bukan sekadar ritual atau hafalan. Bagi keduanya, manusia yang merdeka adalah manusia yang tercerahkan pikirannya.
Kini, dunia menghadapi tantangan baru: krisis kemanusiaan, kesenjangan global, dan pertarungan identitas yang sering kali mengorbankan persatuan. Dalam konteks ini, warisan pemikiran Sukarno dan Ibnu Asyur tetap berdenyut relevan. Dari Sukarno kita belajar bahwa kemerdekaan sejati adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab untuk membangun solidaritas global. Dari Ibnu Asyur kita belajar bahwa hukum—termasuk hukum agama—harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama, bukan sekadar melestarikan tradisi tanpa jiwa.
Sukarno pernah mengingatkan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Seakan menyambung pesan itu, Ibnu Asyur bisa saja berkata, “Dan yang lebih sulit lagi adalah melawan kebekuan pikiran dan ketidakadilan yang dibungkus atas nama agama.” Dari Jakarta hingga Tunis, dari podium Konferensi Asia-Afrika hingga halaman kitab Maqāṣid al-Sharī‘ah, keduanya menyuarakan satu keyakinan yang sama: peradaban yang damai dan adil hanya akan lahir jika kemanusiaan universal ditempatkan sebagai cita-cita tertinggi.