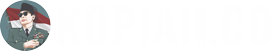Kopiah.co – Gagasan trickle-down effect atau “efek tetesan ke bawah” pernah menjadi teori populer dalam kebijakan ekonomi neoliberal, terutama sejak era 1980-an. Teori ini berasumsi bahwa jika pemerintah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui keringanan pajak dan insentif bagi kalangan kaya dan pelaku usaha besar, maka kekayaan yang terkonsentrasi di atas akan “menetes” ke bawah dalam bentuk investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Namun, seiring waktu, teori ini banyak menuai kritik karena gagal memberikan hasil nyata dalam pengentasan kemiskinan.
Trickle-down effect memiliki akar dalam pemikiran ekonomi klasik dan liberal, yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan semua pihak jika pasar dibiarkan berjalan dengan bebas. Ketika orang kaya dan pelaku usaha besar mendapatkan keuntungan lebih, mereka diyakini akan menginvestasikannya dalam sektor-sektor produktif yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan kelompok bawah.
Kebijakan semacam ini banyak diadopsi di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan Inggris di bawah Margaret Thatcher. Pemangkasan pajak perusahaan, deregulasi, dan privatisasi menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah.
Meskipun pertumbuhan ekonomi kadang meningkat dalam jangka pendek, dampak positifnya terhadap kelompok miskin tidak sejelas yang dijanjikan. Laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan OECD menunjukkan bahwa ketimpangan justru meningkat di banyak negara yang menerapkan model ini. Kekayaan terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara kelompok menengah dan bawah mengalami stagnasi pendapatan atau bahkan penurunan daya beli.
Salah satu kegagalan utama trickle-down effect adalah anggapan bahwa orang kaya akan secara otomatis menginvestasikan keuntungannya demi kepentingan publik. Kenyataannya, banyak dari kekayaan itu disimpan dalam bentuk aset finansial, properti mewah, atau ditransfer ke luar negeri dalam bentuk investasi spekulatif yang tidak menciptakan lapangan kerja lokal.
Lebih jauh lagi, trickle-down effect mengabaikan hambatan struktural yang dihadapi kelompok miskin, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Tanpa kebijakan afirmatif, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan kata lain, membiarkan pasar bekerja sendiri tidak cukup untuk mengangkat kelompok termarjinalkan.
Alternatif: Pendekatan Bottom-Up dan Ekonomi Inklusif.
Sebagai respon terhadap kegagalan model trickle-down, banyak ekonom kini mendorong pendekatan bottom-up yang menekankan pembangunan dari akar rumput, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan kebijakan fiskal yang progresif. Investasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, UMKM, dan perlindungan sosial dianggap lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Ketika pembangunan hanya terfokus pada elite ekonomi, masyarakat desa dan pekerja formal-informal tetap tertinggal. Maka, peran negara dalam mendesain kebijakan pro wong cilik atau rakyat kecil menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial.
Trickle-down effect, meskipun menjanjikan pertumbuhan, telah terbukti gagal dalam mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Ketimpangan yang makin dalam menjadi sinyal bahwa kekayaan tidak otomatis mengalir ke bawah. Maka, sudah saatnya kita mengganti paradigma pembangunan dari yang bersifat elitis menjadi inklusif dan berbasis keadilan sosial. Pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan, harus menjadi arah utama kebijakan ekonomi ke depan.